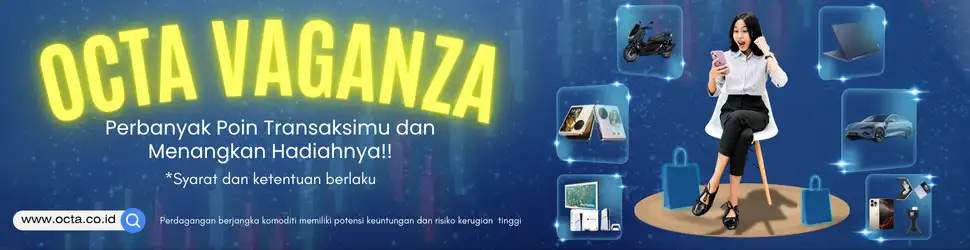Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, baik sebelum diamandemen maupun setelah diamandemen menyatakan: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Bedanya, jika sebelum diamandemen, pasal tersebut disertai dengan Penjelasan, yang antara lain berbunyi “…Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.”, pada pasal 33 setelah amandemen sama sekali tidak disertai dengan Penjelasan. Bung Hatta yang (konon) merupakan konseptor pasal 33 tersebut menafsirkan : “Azas kekeluargaan itu ialah koperasi”. (Lihat: Membangun Koperasi, dan Koperasi Membangun”/PKPN-JR/1971).
Ungkapan Bung Hatta tentang “Azas kekeluargaan itu ialah koperasi” inilah yang kemudian dijadikan rujukan oleh Subiakto Tjakrawerdaya (Menteri Koperasi 1993-1998) dalam memahami koperasi sebagai Koperasi Indonesia. Menurutnya, ide koperasi berasal dari Eropa yang diolah serta dikembangkan oleh Bung Hatta berdasarkan pada Pancasila. Antara Koperasi Indonesia dan koperasi dari Eropa memiliki perbedaan pijakan idiologi yang berlainan, bahkan mungkin bertentangan. Apabila koperasi di Eropa merupakan kerjasama antara individu ataupun perusahaan sejenis yang memiliki tujuan yang sama, bergabung secara sukarela untuk mendirikan koperasi agar dapat bekerja lebih efisien, sehingga mampu bersaing di pasar bebas. Sedangkan Koperasi Indonesia merupakan institusi ekonomi yang sesuai dengan hakekat manusia Indonesia sebagai mahluk komunal (homo socius) sejati,.
Sejalan dengan definisi koperasi Bung Hatta tersebut, menurut Subiakto, koperasi Indonesia dalam memenuhi kebutuhan hidup sejahtera, dilakukan melalui usaha gotong royong berasaskan kekeluargaan. sebagai kewajiban warga negara untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha kooperatif. Aktivitas kerjasama gotong royong seperti ini masih bisa kita saksikan di sejumlah etnis di Nusantara, seperti Subak di Bali, Awig-awig di NTB, Lubuk larangan di Sumatra dan Sasi di Maluku. Cita-cita koperasi Indonesia adalah menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental dengan menciptakan masyarakat Indonesia yang kolektif, berakar pada adat istiadat hidup Indonesia yang asli, seperti gotong royong dan musyawarah, yang dikembangkan pada tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan tuntututan zaman modern.
Masih menurut Subiakto, berbeda dengan Koperasi Indonesia, koperasi di dunia Barat pada umumnya menerima kapitalisme sebagai dasar perekonomiannya, koperasi bertindak sebagai koreksi terhadap tujuan yang tidak kenal batas, yang menjadi pembawaan kapitalisme. Koperasi di sana terutama bertujuan untuk memperoleh pembagian yang adil di dalam perekonomian kapitalis dan untuk mencapai produksi dan penjualan yang lebih rasional di mana badan-badan perantara yang tidak berguna antara produksi dan konsumsi disingkirkan oleh koperasi. Dalam hal ini koperasi di Barat benar-benar melaksanakan prinsip ekonomi.
Lebih lanjut Subiakto, mendefinisikan pengertian Koperasi Indonesia adalah sebagai “perkumpulan orang-orang yang bersatu karena hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis”. Sejalan dengan pengertian tentang Koperasi Indonesia ini, Subiakto mengutip pernyataan Bung Hatta dalam Pidato Radionya pada Hari Koperasi 1969, tentang sifat-sifat koperasi yang terdiri dari: solidaritas, individualitas, self help, mendahulukan kepentingan masyarakat dan tanggungjawab moril dan sosial.
Koperasi menurut ICA
Pengertian tentang koperasi menurut Bung Hatta (dan kemudian “diperluas” oleh Subiakto) mungkin agak berbeda (paling tidak secara redaksionil) dengan pengertian koperasi versi ICA, baik ketika masih menggunakan prinsip-prinsip Rochdale, maupun setelah ICA merumuskan prinsip-prinsipnya sendiri pada 1937, 1966 serta 1995. Meskipun demikian, apa yang disebut sebagai sifat-sifat dan prinsip-prinsip Koperasi Indonesia seperti solidaritas, tolong menolong dan self help, mendahulukan kepentingan masyarakat, tanggung jawab sosial, jika dibandingkan dengan nilai dan prinsip-prinsip yang berlaku universal versi ICA rasanya tidak berbeda jauh apalagi bertentangan, bahkan lebih banyak persamaannya.
Apa yang disebut sebagai “Koperasi Barat/Eropa” adalah koperasi-koperasi yang tergabung dalam ICA (International Co-operative Alliance), yang sebetulnya juga meliputi organisasi gerakan koperasi- di seluruh dunia, termasuk organisasi gerakan koperasi di Indonesia. Organisasi gerakan koperasi Indonesia (Dekopin) menjadi anggota ICA, sejak 1958, meski pada 1 Januari 1965 sempat keluar, dan setelah pemerintahan orde baru (1966) gerakan koperasi kembali menjadi anggota ICA.
Dalam merumuskan Jatidiri Koperasi atau ICIS (ICA Co-opereative Identity Statement) 1995 yang terdiri dari definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi, Dekopin sebagai organisasi gerakan koperasi Indonesia juga ikut serta aktif. Menurut Jatidiri Koperasi ICA 1995 ini, definisi koperasi adalah sebagai berikut: “Koperasi adalah perkumpulan/asosiasi orang yang bersifat otonom yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan yang sama dalam bidang ekonomi, social dan budaya serta aspirasi melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan diawasi secara demokratis.” ( A co-operative is an autonomous association of persons united voleterily to meet their common economic, social and cultural needs and aspiration through a jointly-owned and democratically-controle enterprise).
Definisi tersebut di atas, bersama dengan nilai dan prinsip-prinsipnya, tentu berlaku universal, khususnya untuk organisasi-organisasi gerakan koperasi dan anggotanya yang menjadi anggota ICA. Pada saat ini anggota ICA mencapai jumlah 310 organisasi koperasi, yang terdiri dari 264 anggota penuh dan 46 anggota tidak penuh (associated member). Jumlah ini mencakup sekitar 800 juta orang anggota perorangan dari 107 negara.
Dalam pelaksanaan definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi di negara-negara yang berbeda sistem ekonomi, sosial dan budayanya, tentu tak terhindarkan adanya (bahkan: kuatnya) pengaruh budaya lokal (atau nasional). Sebut saja misalnya koperasi-koperasi di negara-negara Barat (Eropa dan Amerika) yang menganut sistem demokrasi liberal di bidang politik dan kapitalisme di bidang ekonomi, tentu tak bisa lepas dari pengaruh kedua sitem tersebut. Demikian juga di Indonesia, pelaksanaan jatidiri koperasi/ICIS tidak bisa terlepas dari budaya atau tradisi yang sudah berurat berakar seperti gotong royong, kekeluargaan, semangat tolong menolong atau musyawarah untuk mufakat. Dalam praktek perkoperasian berbasis jatidiri koperasi semangat lokal ini sangat terbuka untuk diakomodasi, tanpa melanggar nilai dan prinsip-prinsipnya yang berlaku universal.
Dua Pengertian Dasar
Dalam perkoperasian terdapat dua pengertaian dasar, yaitu prinsip-prnsip dasar koperasi (basic cooperative principles) dan praktek-praktek dasar koperasi (basic cooperative practices). Demikian dinyatakan oleh Sven Ake Book dalam bukunya “Co-operative Values in a Changing World” (1992). Yang termasuk “prinsip-prinsip dasar koperasi” adalah Jatidiri Koperasi (ICIS): definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Sedangkan yang termasuk “praktek-praktek dasar koperasi” adalah semua praktek perkoperasian , yang tidak bertentangan dengan “prinsip dasar koperasi” (Jatidiri Koperasi/ICIS), sebut saja dalam kasus perkoperasian di Indonesia seperti: gotong royong, kekeluargaan, musyawarah untuk mufakat. Termasuk di dalamnya penolakan terhadap individualisme dan kapitalisme, pengentasan kemiskinan, bahkan cita-cita untuk menjadikan koperasi sebagai bagian integral Sistem Ekonomi Pancasila dan sebagai soko guru perekonomian rakyat, semuanya ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang berlaku universal. Selanjutnya hal-hal yang bersifat khas Indonesia ini sudah seharusnya dirumuskan ke dalam praktek perkoperasian sebagai kesepakatan bersama untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi dalam praktek perkoperasian di Indonesia.