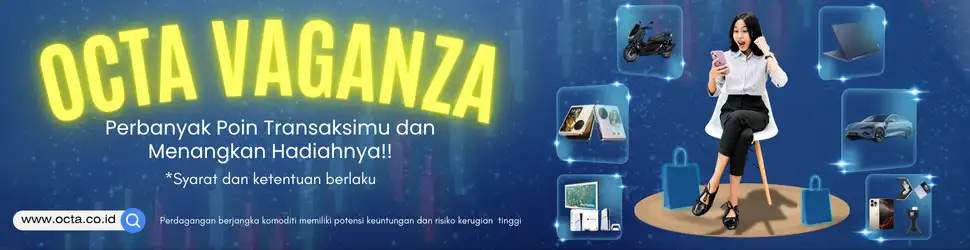INDISCHE Vereeniging, ini perhimpunan anak-anak para pejabat Hindia Belanda yang kuliah di Belanda. Sebuah wadah kongko-kongko, sambil dansa-dansi diselingi minuman keras, dan orasi tanpa wacana politik. Maka, jangan tanya apakah mereka mengenal Saijah dan Adinda anak petani miskin di Lebak Banten itu, atau nasib jutaan petani yang mampus lantaran cultuur stelsel kelas. Tetapi dari perhimpunan yang berdiri pada 1908 inilah mimpi tentang Indonesia merdeka tercetus.
Masuknya sejumlah anak-anak muda kritis, seperti Tjipto Mangoenkoesoemo dan Soewardi Soerjaningrat pada 1913 disusul Mohammad Hatta pada 1921 membuka perubahan besar tentang arti sebuah negara merdeka. Digawangi oleh Hatta pada 1926, perhimpunan ini berganti nama Indonesische Vereeniging, lalu diskursus tentang Indonesia yang berdaulat secara politik dan ekonomi bergulir menjadi sebuah kesadaran kebangsaan. Bahwa sebuah negara yang merdeka harus mampu menata ekonomi sendiri, tak larut dalam dalam arus dagang merkantilistis.
Bangun koperasi model apakah yang akan dipelajari Hatta? Bukankah Aria Wiriaatmaja sudah mengenalkan Hulp en Spaarbank, sebuah bank bercita rasa koperasi? Bukankah pergerakan Boedi Oetomo dan Syarikat Dagang Islam sudah sangat mafhum berkoperasi? Dan bukankah semua tergerus oleh politik kolonial yang memang tak memberi ruang hidup bagi koperasi? Sebab, berkoperasi adalah identik dengan berdemokrasi dan sebuah kesetaraan yang dibangun bersama dari bawah (bottom-up).
Jika kita tengok di negeri asalnya, Inggris, ide koperasi lahir di tengah gemuruh mesin industri kaum kapitalis. Menyeruak di tengah para buruh miskin, yang hak-hak ekonomi mereka terampas oleh maruknya para penyembah harta dan kuasa. Tetapi kesadaran membangun usaha kolektif itu tidak muncul dari lorong gelap dan kumuh para pekerja kelas bawah. Koperasi justru lahir top-down, di tengah selera ‘humor’ kaum kapitalis bernama Robert Owen.
Sebagai kapitalis sejati, Owen, juragan pabrik tenun pertama di Manchester itu mestinya mengusung posisi harta di tempat tertinggi, karena kekayaan menjadi simbol kesuksesan dan kepuasan individu. Itu sebabnya, kata Francis Fukuyama, kapitalisme seringkali merupakan kekuatan-kekuatan destruktif yang menghancurkan kesetiaan dan kewajiban tradisional. Tetapi Owen, punya mimpi lain tentang nilai guna harta. Sang kapitalis itu percaya, hanya dengan cara berkoperasi, kemanusiaan bisa diindahkan.
Hingga Indonesia merdeka, kita masih saja mempelajari penataan koperasi berpola top-down ala kolonial. Bahwa koperasi perlu diatur dan dikendalikan oleh negara ataupun para pemegang modal. Adapun wacana di tengah masyarakat, koperasi hanya badan usaha bersifat sosial yang selalu menunggu bantuan modal pemerintah. Alih-alih badan usaha komersial. Bagi kalangan pemikir koperasi era jadoel, istilah komersial adalah diksi yang tidak sopan karena koperasi sudah terpatri sebagai entitas nirlaba.
Modal koperasi berupa kumpulan orang, namun kata Hans Munkner dalam bukunya, Chances of Co-operatives in the Future, pelayanan optimal terhadap anggota hanya dicapai jika perusahaan koperasi layak secara ekonomi. Dalam konteks itu, koperasi memang tidak menekankan peranan modal bagi kelangsungan usaha. Bagaimana mungkin ? Jawaban bernas kita temui dari Schumacher, penulis buku Small is Beautiful Bahwa pembangunan tidak dimulai dengan barang, tetapi dimulai dengan orang, pendidikannya, organisasinya dan disiplinnya. Tanpa ketiga unsur itu, semua sumber daya akan tetap terpendam dan hanya menjadi potensi belaka.
Yang mengganjal, agaknya karena segala sesuatu yang berbau komersial, acapkali mengorbankan nilai yang bernama kebersamaan. Sementara visualisasi tentang kebersamaan acapkali dipojokkan pada konotasi kaum kiri. Tentu saja kita tidak peduli, ketika tembok Berlin runtuh, terminologi kiri dan kanan itu sudah semakin tidak jelas. Sebagaimana celoteh Presiden Gusdur ketika ditanya: apa tolok ukur bagi koperasi yang dianggap maju. Enteng saja, jika sudah tak perlu lagi bantuan pemerintah. Gitu aja koq repot.●(Irsyad Muchtar)