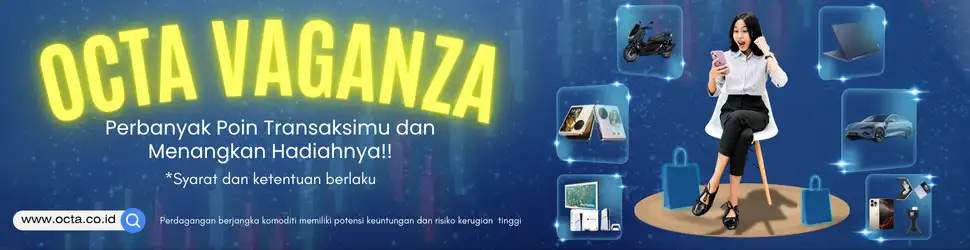“HANYA di puncak gunung aku merasa bersih,” gumam anak muda yang gelisah itu. Lalu gunung demi gunung dilintasinya, menembus kabut, dingin dan lapar. Akhirnya maut merenggut jiwanya di puncak Semeru pada 16 Desember 1969, sehari menjelang usia ke 27. Soe Hok Gie, nama yang melegenda itu tak hanya dikenal di kalangan pencipta alam. Dia juga akrab dengan dunia kecendekiaan dan diskursus idiologi yang anti kemapanan. Sebuah sikap yang sulit dilakukan oleh anak muda sezamannya, angkatan 66 yang belakangan bedol desa masuk ke mesin politik Golkar. Dan Hok Gie, begitu ia biasa dipanggil, memilih hidup di luar kekuasaan, menyeruak di tengah derita rakyat sambil tanpa henti melempar kritik pedas terhadap perselingkuhan kekuasaan.
Kita memang tidak hidup di masa Hok Gie. Tetapi menyimak kembali kegelisahannya terhadap Indonesia. Seolah kita dihadapkan dengan repetisi sejarah, hanya kostum dan pemainnya yang berganti wajah. Hok Gie hidup ketika negeri ini tengah mengalami krisis legitimasi, persekongkolan, nepotisme serta bengkaknya angka korupsi.
Hari saat kematian Hok Gie, di tahun 1969 itu saya masih di bangku SD, yang teringat adalah segelas susu dan kue bulgur yang dibagikan seminggu dua kali di sekolah. Anak-anak harus cerdas dan banyak minum susu agar sehat dan pintar, kata pak guru seraya menyitir idiom latin ‘Mens sana in corpore sano’. Saya tidak tahu dari mana sekolah bisa membagikan susu dan bulgur secara gratis, karena minum susu waktu itu merupakan kebanggaan tersendiri. Susu hanya konsumsi orang-orang berduit. Tatkala, saya berangkat dewasa mengikuti langkah Hok Gie di medan-medan pendakian gunung dan menyimak kisah hidupnya yang keras di tengah kesepian. Saya pun mafhum tentang kegelisahan itu. Bahwa negeri yang gemah ripah loh jinawai ini hidup di tengah lilitan utang, sementara investasi asing merangsek ke dalam negeri, dan pembangunan menjadi icon rezim Orde Baru.
Setelah lebih dari empat dasawarsa, kegelisahan Hok Gie tak kunjung selesai. Kita masih tetap dihadapkan dengan masalah yang sama. Utang luar negeri terus menumpuk, politisi sibuk berebut kursi, pekerja wanita kita dibiarkan jadi babu di negeri orang dan angka pengangguran kian absurd. Tentu tak kita pungkiri bahwa di rentang waktu yang panjang itu sudah banyak yang dinikmati dari hasil membangun. Tetapi, kata Schumacher, pembangunan hanya menjadi kesia-siaan tanpa mengacu pada pendidikan, organisasi dan disiplin. Tanpa ketiga unsur ini, semua sumber daya akan tetap terpendam dan hanya jadi potensi kosong. Schumacher, penulis Buku Small Is Beautiful itu, menyentuh kemiskinan sebagai persoalan dua juta desa, dua miliar jiwa. Kita gagal menangkap semua inti masalah, jika terus memandang pembangunan dari segi kuantitatif dan abstraksi raksasa seperti GNP, penanaman modal, tabungan dan hitungan angka lainnya yang cuma berguna untuk negara maju. Padahal, masyarakat yang lapar tidak cukup sekadar diberi ikan, tapi diajari cara membuat kail.
Tetapi kita terlambat mencermati perubahan global itu. Kerakusan kaum kapitalis membuat kekayaan bumi hanya milik segelintir orang. Kemiskinan di dunia ketiga tak bergeser dari tentang tiga miliar manusia yang hidup di bawah 2 dolar sehari. Sebuah penelitian Infid dan Oxfam menyimpulkan empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan setara dengan 100 juta penduduk. Sepanjang penguasaan terhadap aset-aset produktif tak dibagi secara luas ke tengah masyarakat, maka kesenjangan kaya-miskin bakal terus melebar.
Tesis tentang kemiskinan dunia ketiga selalu menggugah kita untuk berontak terhadap ketidakadilan itu. Saat mengulas pemikiran Hok Gie, Kuntowijoyo sempat berguman, andai Hok Gie berumur panjang apakah ia juga akan seperti kebanyakan aktivis lainnya, ketika berusia 25 tahunan amat idealis dan radikal tapi pada usia 40 tahunan menjadi kompromis. Hok Gie memang harus pulang lebih awal. Biarkan ia tegak sebagai sejarah dari potret seorang demonstran muda yang kesepian. (Irsyad Muchtar)