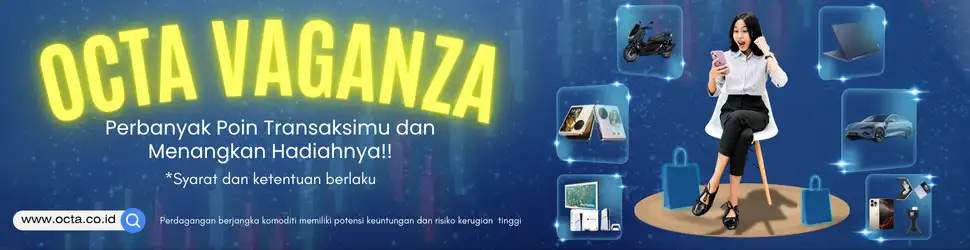MEREKA, para pejuang revolusioner Kuba itu, memanggilnya Che. Sebuah sapaan akrab khas Argentina yang menjalar di belahan Amerika Latin. Wajahnya yang khas, jenggot dan kumis lebat dengan topi baret di kepalanya terpampang abadi di gedung pemerintahan Kuba. Waktu yang bergulir lebih dari lima dasa warsa itu seolah tak hendak menggerus wajah Ernesto ‘Che’ Guevara de la Serna.
Ketika tentara Bolivia mengakhiri hidupnya di bulan Nopember 1967, orang-orang kiri di seantero dunia turun ke jalan, menangisi dokter yang memilih berhenti praktek demi revolusi itu. Simbol perlawanan itu telah tiada, tapi wajah Che muncul di mana-mana. Di kaos oblong, di gantungan kunci, di sebuah pub hiburan malam dan di dinding kamar seorang aktivis mahasiswa. Ia menjadi icon kegelisahan kaum muda atas ketidakadilan.
Dan di Havana, sampai hari ini Che adalah sebuah cita-cita. Setiap Jumat pagi, anak-anak sekolah dasar di kota itu, dikumpulkan oleh gurunya di aula sekolah. Mereka berbaris rapi menyanyikan lagu kebangsaan dan memberi hormat kepada bendera negara. Setelah itu mereka berikrar, “….Kami akan seperti Che,”
Ada rasa bangga tentang Che di sana. Tentang seorang asing yang datang untuk membebaskan penindasan. Che di Kuba adalah simbol bagi sebuah kejujuran, keberanian dan internasionalisme.
Simbol itu juga menjalar ke negeri ini. Sosok Che bukanlah mahluk asing bagi pergulatan kaum muda kita. Setelah Bung Karno, kita mungkin sulit menyebut tokoh sejarah masa lalu yang mampu menjadi bingkai motivasi kaum muda. Yang muncul justru wajah penyanyi Iwan Fals yang memang kerap menyuarakan kebobrokan penguasa.
Dalam rentang dua dasa warsa sejak reformasi bergulir, apakah kita semakin bangga dengan negeri ini? Ah.. pertanyaan ini terasa menyesakkan dada. Begitu sulit untuk menyebut sebuah rasa bangga di zaman ketika kursi parlemen bisa dibeli dengan sepotong kaos kampanye, nasi bungkus dan goyang penyanyi dangdut. Ketika hukum dan perundang-undangan berpihak pada pemilik uang dan ketika ribuan tenaga kerja kita di luar negeri (TKI) diperas tanpa upah dan diperkosa tanpa protes. Kita tega menyebut mereka dengan ‘komoditas ekspor’ yang nyatanya memang mampu menyumbang devisa lebih dari Rp 100 triliun per tahun. Remitansi TKI pada 2017 mencapai Rp 119 triliun, menyumbang satu persen dari produk domestik bruto Indonesia.
Menjadi bangga dan tidak bangga terhadap negeri sendiri hanyalah temporer. Sebab bangga itu sendiri merupakan identitas dari rasa berkebangsaan kendati acap kali ditutupi. Pengusaha Jepang, Akio Morita, harus menyembunyikan kebanggaan terhadap negerinya ketika ia membangun Sony. Selain namanya yang ke barat-baratan, bandingkan misalnya dengan Toshiba (Tokyo Shibaura Eelctronic Company), Morita juga terpaksa menulis sekecil mungkin lebel Made in Japan dalam produk Sony. Masalahnya, tahun 50-an itu, produk Jepang identik dengan mutu rendah. Di Eropa, Jepang hanya dikenal sebagai negeri produsen origami. Masalahnya, bagi Morita, bukan soal nasionalisme itu. Ia hanya ingin pasar tidak menghakimi produk Jepang lebih dini sebelum menguji mutunya. Ketika Sony membuat radio transistor mini pada 1955 seharga US$30, sebuah perusahaan ternama di AS, Bulova, berniat memborong 100.000 unit. Sebuah pembelian yang luar biasa untuk sebuah perusahaan belum ternama.
Tetapi Morita menolak, lantaran Bulova meminta radio itu diberi merk Bulova. Keputusan itu disesalkan oleh rekan-rekan Morita. Tetapi, kalau saja waktu itu Ia mau menjual produknya dengan merk orang lain, barangkali hingga kini kita tidak mengenal Sony Corporation. Di China, kebanggan itu direpresentasikan oleh Jack Ma, Guru bahasa Inggris di Hangzhou yang kini pengusaha e-commerce terbesar ini berhasil menggeser frasa melecehkan itu. Dari Made in China menjadi Bought In China. (Irsyad Muchtar)