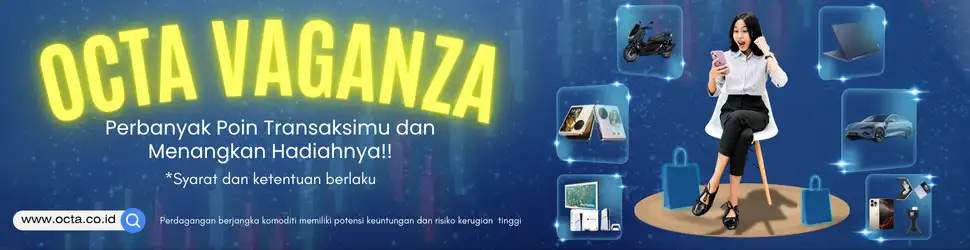Dikenal sebagai wong samin atau wong kalang. Mereka lebih suka disebut wong sikep. Saminisme adalah pembangkangan terhadap imperialis, lalu menyingkir. Isolasi itu mulai terbuka tahun 70-an.
DI RUMAH duka seorang pemuka desa. Suatu hari. Di tengah kerumunan pelayat, nyelonong seorang laki-laki tua. Usianya sekitar 75 tahun. Ia mengenakan baju kurung lengan panjang warna hitam; dengan celana selutut, juga berwarna hitam. Sarungnya diselempangkan di bahu kiri. Caping-nya yang terbuat dari daun lontar dibuka, ditempelkan di dada kiri. Di atas kepala melilit udeng (ikat kepala) motif batik, warna hitam kecokelatan.
Dengan sangat percaya diri, ia memasuki rumah menuju ke tempat jenazah disemayamkan. Tanpa menoleh ke kanan atau ke kiri, apalagi sekadar basa basi tegur sapa. Ia seolah tak kenal siapa pun, meski beberapa yang hadir mengenali lelaki itu. Lurus lempeng ke posisi jenazah. Setiba di sosok terbujur kaku itu, ia buka tutup bagian atas sembari menatap wajah mayit. Ia menyatakan belasungkawa, dengan cara yang tak biasa.
“Sedulur, asalmu ora ono/Terus dadi ono/Saiki ora ono meneh/Yo wis, tak dongak-ke slamet.” (Saudara, asalmu tidak ada/Lalu menjadi ada/Sekarang tidak ada lagi/Ya sudah, saya doakan selamat). Lelaki tua itu adalah seorang Samin. Gampang dikenali dari pakaiannya. Lelaki biasanya menggunakan baju lengan panjang tanpa kerah warna hitam, wanita menggunakan kebaya. Mereka tidak diperbolehkan menggunakan celana panjang.
Masyarakat Samin adalah komunitas keturunan para pengikut Samin Soerosentiko. Inti ajarannya sedulur sikep, berwaspada atas segala sesuatu. Kiayi Samin dan orang-orang yang sepaham inilah yang mengobarkan semangat melawan terhadap puak Belanda sang penjajah. Bentuknya bukan kekerasan fisik. Agak mirip dengan ahimsa Gandhi, tapi lebih frontal. Modus yang dipraktikkan adalah menolak membayar pajak, menolak segala peraturan yang dibuat pemerintah kolonial. Mereka tak sudi patuh pada aturan bikinan puak penjajah.
Al kisah, di tahun 1907, Bojonegoro geger. Tokoh masyarakat asal kota tembakau itu, Samin Soerosentiko, ditangkap Pemerintah Hindia-Belanda. Kiayi Samin dianggap mempengaruhi masyarakat sekitar dengan semacam ajaran, yang intinya pembangkangan. Ajaran ini di kemudian hari disebut Saminisme. Ekses langsung ajaran perlawanan tersebut membuat pemerintah kolonial Hindia-Belanda kesulitan menancapkan pengaruhnya di Bojonegoro.
Kiayi Samin Surosentiko lahir di Ploso, wilayah Blora, Jawa Tengah, tahun 1859. Ia ditangkap oleh penguasa kolonial karena membangkang bayar pajak dan tidak sudi ikut kerja paksa. Ia dibuang ke Sawahlunto, Sumatera Barat, hingga wafat di sana tahun 1914. Pemimpin Suku Samin, Hardjo Kardi, adalah trah terakhir Samin Soerosentiko. Meski dituduh sebagai tukang demo, ia jamin kampungnya aman dari kasus tindak pidana kriminal, terutama pencurian dan kekerasan.
Sejak dikenal secara umum, dari zaman Belanda, orang Samin bermukim menyebar di daerah Bojonegoro, Tuban, Blora, Rembang, Grobogan, Pati, dan Kudus. Mereka menghuni wilayah perbatasan. Jumlah mereka sebenarnya tidak banyak. Orang Samin memilih kawasan Pegunungan Kendeng di perbatasan Provinsi Jateng dan Jatim sebagai lingkungan untuk survival.
Mereka berdomisili tidak bergerombol, melainkan terpencar-pencar dalam unit-unit kecil. Misalnya, tiap desa terdapat 5-6 keluarga, tetapi solidaritas sosial mereka menyatu dengan kuat. Guyub khas masyarakat tradisional. Gemeinschaft. Dibandingkan dengan kisah lama tentang Suku Samin yang berada di Dusun Jipang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro, kini kampung Samin sudah jauh lebih modern.
Suku Samin hidup dengan cara yang amat sederhana, enggak neko-neko. Mereka lebih suka disebut wong sikep, karena kata samin dianggap bermuatan makna negatif. Jiwa mereka polos dan terbuka. Apa adanya, selugu kebanyakan suku-suku tertinggal dan tercecer dari modernisasi peradaban. Mereka berbicara menggunakan bahasa Kawi bercampur bahasa Jawa rendah, ngoko.
Jalinan rasa kolektivitas tercermin dari kalimat sederhana, Ono niro mergo ningsun, ono ningsun mergo niro. (Adanya saya karena kamu, adanya kamu karena saya). Pengayatan filosofis semacam itu menunjukkan mereka sesungguhnya memiliki solidaritas organik yang tinggi. Orang Samin sangat menghargai eksistensi manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial.
Dekat dan menyatu dengan alam, pandangan orang Samin terhadap ekologi dan ekosistem juga menarik. Ucapan seperti: Banyu podo ngombe/Lemah podo duwe/Godong podo gawe. (Air sama-sama diminum/Tanah sama-sama (kita) punya/Daun sama-sama memanfaatkan) menjelaskan tentang pentingnya sharing di tengah kesadaran kolektif. Dalam hidup, mereka tidak bergantung kepada teknologi maju. Orang Samin itu mandiri dengan pemberian dan berkah alam sekitar mereka.
Saminisme secara sederhana bisa diartikan sebagai ajaran kejujuran untuk mencapai kemuliaan. Lantaran kejujuran itu pulalah, penganut Saminisme tidak bisa dimasuki skenario politik pecah belah (devide et ampera) pemerintah Hindia-Belanda. Oleh puak kolonialis, Samin dan penganutnya dianggap mengganggu jalannya pemerintahan dan tata kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, saminisme bukanlah ajaran pesimistis, melainkan ajaran yang kreatif dan berani.
Sebutan lain selain wong sikep adalah wong kalang. Mengapa? Sebab, bagi orang di luar komunitas Samin, fenomena suku Samin dalam banyak hal merupakan fenomena yang ganjil. Baik itu menyangkut ketidakrasionalan pikiran, keeksentrikan perilaku, maupun ketidaknormalan bahasa. Khususnya jika dibandingkan dengan etnis Jawa sebagai induk kultural mereka.
Isolasi masyarakat Samin mulai terbuka tahun ’70-an. Mereka baru tahu Indonesia telah merdeka. Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Bojonegoro, Mohamad Farhan, sejauh ini, komunitas suku Samin di Dusun Jipang masih sangat sulit disentuh provokasi berlatar sentimen agama. Islam kini sudah hampir menjadi agama mayoritas di kalangan wong Samin. Namun, segelintir orang Samin masih bertahan dengan keyakinannya sebagai wong sikep—ajaran inti Samin Soerosentiko.●(dd)