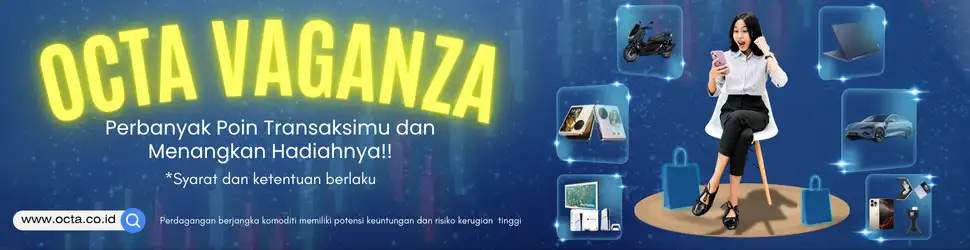Suku minoritas Orang Rimba atau Suku Anak Dalam (SAD) menghuni Provinsi Jambi dan Sumbar. Terdapat beberapa sebutan lain bagi Suku Anak Dalam (SAD), seperti Suku Kubu, Orang Rimba, atau Orang Ulu. Sebagai komunitas organik, mereka memiliki identitas khas berdasarkan tradisi dan adat. Mereka dikenal sebagai penghuni dan pelestari hutan. Mereka ditemukan tersebar di Kabupaten Merangin, Bungo, Tebo, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, dan Batanghari (Prov Jambi), selain di Kabupaten Dharmasraya (Sumbar).
Sebutan Suku Anak Dalam tidak hanya ditujukan untuk Orang Rimba, tapi juga ditujukan kepada komunitas atau suku lain yang terdapat di Jambi, yaitu Batin Sembilan dan Talang Mamak yang pola hidupnya ada kemiripan. Hanya saja, kedua suku ini hidup relatif menetap dan menerapkan sistem pertanian petalangan sebagai sumber penghidupan mereka.
Dalam tradisi lisan disebutkan SAD berasal dari Maalau Sesat. Nenek moyang mereka melarikan diri ke hutan rimba di Air Hitam. Versi pendapat lain, SAD berasal dari Pagaruyung, yang ditandai dengan dianutnya sistem kekerabatan matrilineal. Versi lain lagi, Orang Rimba berasal dari sisa-sisa pasukan Kerajaan Sriwijaya yang kalah berperang melawan Belanda, lalu melarikan diri ke hutan. Dugaan-dugaan ini tak cukup meyakinkan.
Kemungkinan paling ilmiah, Orang Rimba berasal dari suku Melayu Proto atau “Melayu Asli”, masuk golongan Austronesia yang berasal dari Yunnan. Kelompok Melayu Proto inilah yang berpindah ke Asia Tenggara pada Zaman Batu Baru (2500 SM). Mereka sampai di dataran Jambi. Mereka sudah mengalami proses perubahan sosial ribuan tahun, tapi kebanyakan terisolasi di dalam hutan. Ketika budaya Hindu, Buddha dan Islam masuk, mereka tidak tersentuh sama sekali. Mereka tidak mengalami transformasi perubahan sosial.
Di antara mereka masih ada yang menggunakan cawat dan kemben untuk menutupi organ vital. Beberapa kelompok kecil sudah mulai mengenakan celana bahkan baju. Mereka mengenal sistem kepemimpinan yang berjenjang, mulai dari Temenggung, Depati, Mangku, Menti, dan Jenang. Suku Anak Dalam penganut kepercayaan animisme, walau ada juga yang telah memeluk agama Islam. Anak laki-laki yang sudah kawin harus tinggal di lingkungan kerabat istrinya.
Secara turun-temurun, SAD hidup dalam kelompok-kelompok kecil (rombong) di dalam kawasan hutan dan sampai tahun 1970-an masih hidup dalam fase berburu dan meramu. Berburu dan meramu adalah DNA Orang Rimba. Mereka merupakan salah satu suku minoritas yang hidup dalam keadaan miskin yang sangat ekstrem di Sumatera.
Seiring berjalannya waktu, terdapat perubahan yang mengusik kehidupan masyarakat SAD. Perubahan fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan besar-besaran membuat hasil hutan yang menjadi penghidupan masyarakat SAD tergerus dan menyusut secara hebat. Ditambah lagi dengan penggunaan aliran anak sungai yang berubah menjadi kanal untuk mengairi perkebunan. Alhasil, kondisi masyarakat SAD yang juga kerap berburu ikan itu terdampak secara parah.
Perkebunan sawit, transmigrasi dan pembangunan infrastruktur jalan lintas tengah telah dan makin memiskinkan Orang Rimba. Agak tertolong sedikit karena jangkauan ruang hidup Orang Rimba sangat luas. Soalnya, mereka menerapkan budaya nomaden dan tradisi melangun. Melangun berarti hidup mengembara ke dalam hutan. Jika tiba waktunya, tak peduli pohon durian sedang berbuah lebat, ada hewan buruan lewat, getah karet siap disadap, atau ikan sedia ditangkap, semua itu akan ditinggalkan. Isyarat untuk itu datang tatkala anggota kerabat SAD yang mati. Itu tanda panggilan melangun telah tiba.
Di tengah derap transmigrasi dan perkebunan massal, jumlah tutupan hutan menyusut drastis. Kawasan hutan alam bahkan nyaris menghilang. Orang Rimba terusir dari rumah dan kebun mereka sendiri. Mereka kehilangan harkat martabatnya sebagai manusia, tercerabut dari akar budaya leluhur, dan termarjinalkan dari pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara. Kini ada yang terpaksa tinggal di tengah-tengah kebun sawit dan kebun karet karena semakin sulit untuk berburu, berkebun atau mendapatkan tanaman obat yang semula disediakan oleh alam. Mereka termarginalkan dan tak berdaya.
Orang Rimba kepada generasi muda mereka, untuk meneguhkan tradisi. Seloka itu berbunyi, “Semenjak nenek puyang kami nio, Orang Rimbo beratap cikai, bedinding banir, berayam kuaw, bekambing kijang, bekebau tonuk.” Seloka sederhana ini bermakna dalam. Ia menggambarkan pembagian ruang antara Orang Rimba dan ‘orang terang’, agar tidak saling ganggu dan bertoleransi dalam sebuah harmoni, sejak dahulu kala.
Ruang hidup Orang Rimba dijaga dengan penuh kehati-hatian, kesyukuran dan kecintaan. Banyak sekali aturan, bahkan penyakralan, terhadap alam. Mereka lebih suka tinggal di pondokan (biasa disebut sudung) beratap terpal atau plastik hitam untuk memudahkan mobilitas saat tiba panggilan melangun. Sudung dulunya beratapkan daun puar, tanpa dinding dan lantai.
Pengetahuan Suku anak Dalam yang terakumulasi dari generasi ke generasi janganlah hilang karena hilangnya hutan yang menjadi penyangga hidup mereka. Pengetahuan itu dari mulai jenis dan komposisi tanaman obat hingga teknik meracik obat berbahan dasar tanaman yang tumbuh di sekitar hutan.
Tradisi gotong royong, jaga sesama, juga tak asing bagi komunitas Suku anak Dalam si Orang Rimba. Siapa pun yang beruntung mendapatkan hewan buruan, maka hewan tersebut akan dibagi rata ke semua anggota rombong. Begitu juga dengan kepemilikan bahan makanan pokok seperti beras, secara otomatis akan dikonsumsi bersama-sama.
Namun, yang Namanya perubahan adalah sebuah keniscayaan sejarah. Mesti dan tak terelakkan. Mau tak mau, masyarakat SAD telah, tengah dan terus bertransformasi. Program Peduli—diinisiasi sebuah upaya serius dari kelompok pemberdayaan masyarakat adat yang terpinggirkan—percaya bahwa pasca pendampingan, masyarakat SAD mempunyai pilihan. Mereka mampu merespons “halom nio la berubah”, perubahan alam semesta ruang hidup mereka, dengan pilihan sadar.
Sejatinya, Orang Rimba unggul dalam kearifan memahami hukum alam, membaca hutan, dan memperlakukan ruang hidup dengan penuh kesyukuran–“Alam terbentang jadi guru”. Jika Orang Rimba tak lagi berburu dan meramu, terasing dari habitat asli mereka, siapakah yang benar-benar akan menjaga rimba? Ketika Orang Rimba kehilangan rimba, mereka kehilangan cara hidup, budaya dan sistem kepercayaan; diam-diam bencana ekologis mengintai dari sejumlah arah.●(Zian)