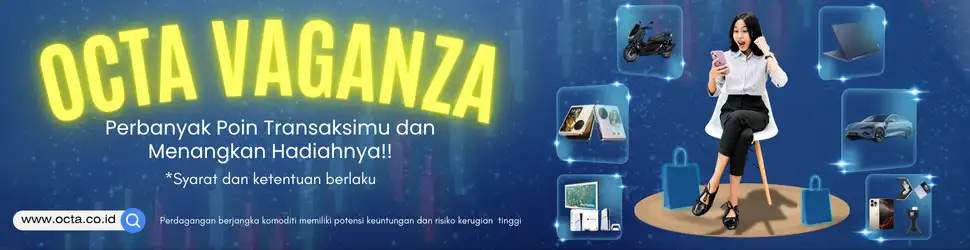Seorang mahasiswa tewas diberondong peluru aparat pemerintah di depan Istana Merdeka Jakarta. Arief Rahman Hakim nama mahasiswa itu. Ia gugur sebagai martir namun tidak sia-sia karena sebuah rezim berhasil ditumbangkan. Peristiwa yang dikenal dengan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) di tahun 1966 itu menjadi simbol perlawanan dan koreksi masyarakat kampus terhadap pemerintahan yang lengah. Gerakan mahasiswa turun ke jalan mengafirmasi peran mereka sebagai agen perubahan sosial (agent of social change).
Apakah artinya kematian itu, jika dalam setiap pergerakan mahasiswa selalu saja ada lawan yang tidak imbang antara batu dan peluru? Di Tiananmen pada Juli 1989, para mahasiswa berhadapan dengan puluhan tank tantara. Aksi demo selama enam pekan itu berakhir dengan pembantaian lebih dari 3.000 orang mahasiswa. Mereka tewas demi sebuah tuntutan kebebasan politik yang lebih besar, demokrasi di China tak pernah lahir. Tapi, apalah juga arti demokrasi jika berjalan tanpa jiwa. Boleh jadi kita sepakat dengan ungkapan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan paling buruk; terlalu bergantung pada suara mayoritas yang sering kali tidak didasari pengetahuan dan rasionalitas, hanya melulu emosi dan opini populer. Tapi, keluh Winston Churchil, tidak ada yang lebih baik dari itu.
Mengapa kekuasaan berubah bengis dan represif setelah mereka mengonsolidasikan kontrol atas masyarakat? Pertanyaan ini menjadi sebuah kebimbangan. Seperti kebimbangan Taufiq Ismail saat menghantar jenazah rekannya itu ke peristirahatan terakhir. Dalam sepotong puisinya “Sebuah Jaket berlumur Darah” tersurat keraguan bahwa perjuangan moral ini hanya akan menabrak tembok kekuasaan yang angkuh.
Akan mundurkah kita sekarang Seraya mengucapkan ‘Selamat tinggal perjuangan’
Berikrar setia kepada tirani dan mengenakan baju kebesaran sang pelayan?
Setelah empat dasa warsa berlalu, gerakan mahasiswa tetap seperti sediakala, simbol penjaga moral yang tetap sama. Mahasiswa masih gemar turun ke jalan dan memampang spanduk di depan gedung DPR tempat para anggota legislatif bersidang merancang Undang Undang. Ironisnya, yang mereka hadapi kini para mantan mahasiswa yang di zamannya juga para pendemo yang tegar menjaga moral bangsa.
Apa yang salah? Tidak ada, karena inilah siklus kehidupan di mana setiap orang sering gamang saat dihadapkan pada kursi kekuasaan, kelimpahan harta dan birahi seksual.
Mereka yang dipanggung kuasa itu, oleh Ibnu Khaldun dikenali sebagai kelompok Hadarah; kelas mapan dengan ikatan sosial yang renggang. Pada kutub lainnya ada kelompok Badawah; mewakili masyarakat pinggiran, terbelakang bahkan primitive namun dari solidaritas kuat.
Dalam teorinya tentang kebangkitan dan runtuhnya sebuah negara, Khaldun menganalogikan Hadarah pada sosok penguasa yang pada awalnya adalah kaum Badawah yang merangsek untuk merebut kekuasaan negara. Ironisnya, ketika mereka memenangi perjuangan tersebut, Badawah berubah perilaku menjadi penguasa baru yang juga zalim. Tentu saja ada sejumlah pengecualian di mana mereka tetap menjaga marwah perjuangannya sebagai idiolog Badawah. Namun sebagian besar lainnya bergeser menjadi Hadarah baru, penguasa yang halalkan banyak cara dengan prilaku Machiavellian. Kemudian muncul lagi arus Badawah baru yang merongrong kekuasaan mereka. Begitulah siklus jatuh bangun kekuasaan berlangsung sepanjang sejarah umat manusia.
Seperti yang kita cermati pada gerakan mahasiswa 1998 yang melahirkan reformasi, sejatinya adalah gerakan melawan para senior mereka, para mahasiswa angkatan 66 yang terlena duduk di kursi kekuasaan. Demikian pula dengan gerakan-gerakan yang lahir kemudian saling datang silih berganti mengikuti siklus teori kekuasaan Khaldun.
Lalu akan berhentikah kita dengan terminologi tentang kuasa dan makna demokrasi yang naif itu? Ada jawaban menggelitik dari Yuval Noah Harari. Sebagai spesis Homo Sapiens, manusia adalah makhluk yang bijaksana. Masalahnya sejauh mana kita berhasil menyandang nama tersebut dengan pantas.