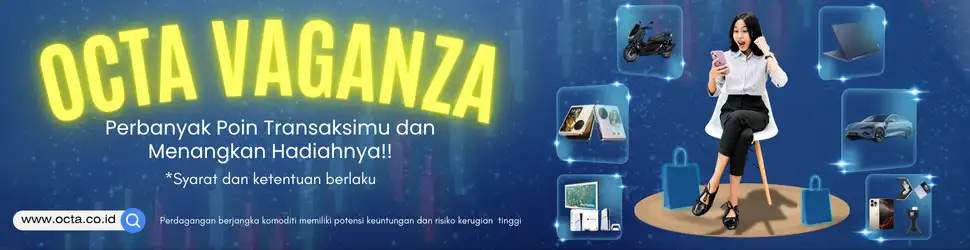Oleh: Irsyad Muchtar*
Apa yang sebenarnya terjadi pada Jumat pagi, 17 Oktober 1952, ketika moncong-moncong meriam mengarah ke Istana Merdeka, Jakarta? Hari itu, sekitar tiga puluh ribu demonstran yang dikawal tentara Angkatan Darat mengepung Istana Merdeka, mengejutkan Presiden Sukarno yang tengah berolahraga pagi.
Kemal Idris, Komandan Divisi Tujuh Siliwangi, mengerahkan satu batalion artileri lengkap dengan empat meriam yang mengelilingi halaman istana. Spanduk besar terbentang di tengah kerumunan massa bertuliskan “Bubarkan Parlemen!”. Poster-poster lain bertuliskan “Parlemen Bukan Warung Kopi!”, “Mana Beras?”, dan “Berantas Korupsi!”, mencerminkan sulitnya kondisi ekonomi kala itu.
Ketegangan antara sipil dan militer meningkat, terutama karena parlemen dinilai terlalu banyak mengintervensi urusan militer, sementara pemilu untuk memilih anggota DPR definitif tak kunjung dilaksanakan.
Tujuh panglima daerah yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution menghadap Presiden Sukarno. Mereka mendesak agar DPRS dibubarkan, namun Sukarno dengan tegas menolak karena tidak ingin dicap diktator. Ia malah menuduh militer telah melakukan “kudeta kecil” dengan memamerkan kekuatan senjata di depan istana.
Dalam otobiografinya yang ditulis Cindy Adams, Sukarno mengenang:
“Dengan tenang aku berjalan menuju massa yang tengah beringas itu. Alih-alih gemetar ketakutan di bawah moncong-meriam, aku menatap langsung ke mulut senjata dan melampiaskan kemarahan pada mereka yang mencoba membunuh demokrasi dengan pasukan bersenjata.”
Pidato Sukarno yang menggelegar berhasil merebut hati massa. Kerumunan pun perlahan membubarkan diri sambil meneriakkan yel-yel “Hidup Bung Karno!”
Seperti dikatakan ilmuwan politik Herbert Feith, Sukarno adalah tipologi pemimpin solidarity maker — sosok yang mampu menggalang dukungan massa — sedangkan Mohammad Hatta lebih mencerminkan tipe administrator.
Kudeta “setengah hati” itu akhirnya gagal. Nasution dipecat, sementara Kemal Idris—mayor muda yang berani—dikandangkan. Ia kehilangan promosi selama 13 tahun hingga tahun 1965, ketika Soeharto memberinya kesempatan untuk membalas.
Pada 11 Maret 1966, saat Sukarno memimpin rapat Kabinet Dwikora II yang dijuluki “Kabinet 100 Menteri”, Kemal Idris mengerahkan satu peleton pasukan RPKAD tanpa tanda pengenal untuk mengepung Istana. Ribuan mahasiswa yang membawa spanduk Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) turut bergerak mendesak masuk ruang sidang.
Aksi mahasiswa, yang mendapat perlindungan dari TNI AD di bawah Kemal Idris, Sarwo Edhi, dan Ali Murtopo, makin memanas setelah salah satu rekan mereka, Arif Rahman Hakim, tewas tertembak—menjadi martir pertama gerakan mahasiswa Indonesia.
Sukarno panik menyadari kekuasaannya di ujung tanduk. Ia segera meninggalkan ruang sidang dan terbang ke Istana Bogor dengan helikopter. Kabinet 100 Menteri pun kocar-kacir.
Kemal Idris berhasil mengantarkan Soeharto ke tampuk kekuasaan. Namun di awal Orde Baru, popularitasnya di kalangan muda membuat Soeharto waspada. Kemal kemudian “dibuang” sebagai Panglima Wilayah Indonesia Timur, dan akhirnya bergabung dengan kelompok Petisi 50, menentang otoritarianisme Soeharto.
Apakah sejarah akan berulang? Mungkin kita dapat belajar dari Revolusi Prancis: gerakan yang awalnya mengusung kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, pada akhirnya justru melahirkan pemerintahan teror dan penindasan baru—seperti yang terjadi pada era Napoleon Bonaparte. (#)
*)Pimpinan Redaksi Majalah Peluang