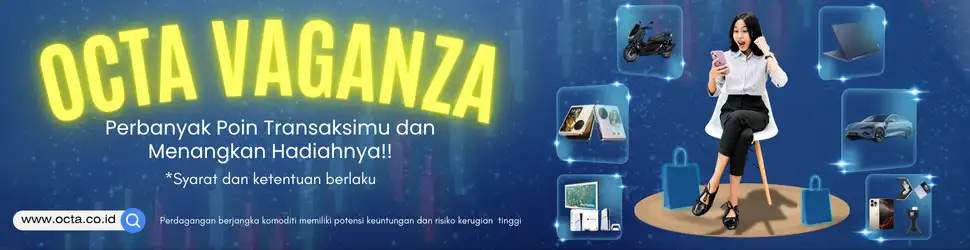Kolonialisme Barat barangkali sudah lama lewat. Era ketika sebuah bangsa membangun kesejahteraan negerinya dengan menjarah negeri lain; sah-sah saja tanpa perasaan bersalah. Bahkan wacana-wacana ilmiah Barat, terus berupaya melegitimasi agresi di masa lalu itu sebagai sebuah pembenaran.
Berakhirkah era kelam itu di abad digital ini? Nanti dulu, galibnya bangsa kemaruk tak akan pernah berhenti menggasak hak orang lain. Kolonialisme dalan ujudnya yang lain tetap tumbuh dengan berbagai merk dan cita rasa modernitas. Boleh jadi benar apa yang disinyalir Ania Loomba dalam Colonialism/Postcolonialism bahwa kolonialisme sebagai keniscayaan yang berulang, yang tersebar luas dalam sejarah manusia. Ia bisa berbentuk negara, personal atau lembaga berbaju sosial keagamaan. Tetapi semangatnya tidak berubah, menjarah ekonomi bangsa lain.
Begitulah cara kaum kolonial berganti kulit menjadi kapitalis. Ketergantungan terhadap tanah, ekonomi hingga kebudayaan menjadi lapangan bermain yang harus diperangi. Ekonomi kapitalis menempatkan bisnis sebagai perang. Seperti kata Jack Trout, dalam perang semua orang ingin merampas bisnis orang lain, maka semua pesaing harus dianggap sebagai musuh.
Tentu saja, belahan Barat tidak melulu rumahnya kaum kolonial berbaju kapitalis. Kita beruntung masih ada model Robert Owen (1771-1858). Pemilik pabrik pemintal kapas di Manchester Inggris ini adalah kapitalis berwatak sosialis dan penggagas gerakan kaum buruh. Owen sangat percaya bahwa hanya sistem koperasi yang mengindahkan kemanusiaan. Ia tidak pernah berhenti mengampanyekan kebajikan-kebajikan berkoperasi yang pada gilirannya melahirkan cikal bakal gerakan koperasi pertama, Rochdale Society pada 1844.
Konsep ekonomi tanpa persaingan saling menggilas itu belakangan direduksi oleh Adam M Brandenburger dan Barry J Nalebuff ketika mengintrodusir Co-opetition di tahun 1996. Kata kedua profesor dari Harvard Business School dan Yale School of Management ini, pemikiran tentang perusahaan yang selalu berperang dengan pesaing adalah terlalu sederhana. Bukankah lebih baik, jika keduanya sama-sama menang.
Padanan co-opetition memang belum kita temukan dalam kamus bahasa Inggris terbaru. Intinya adalah bagaimana sebuah persaingan usaha dapat berlangsung dengan tidak saling mengalahkan.
Ben Lutkevich, penulis teknis dari Whatls.com menyimpulkan co-opetition adalah strategi untuk menghindarkan pesaing dari zero-sum game, di mana pemenang mengambil semua dan yang kalah dibiarkan pulang dengan tangan kosong. Model Nilai Bersih menggantikan pendekatan itu dengan plus-sum game, sehingga hasilnya menguntungkan semua pesaing ketika mereka bekerja sama. Strategi ini memang bukan sesuatu yang baru, kendati secara individu masih banyak korporat besar yang merasa unggul jika bermain sendiri. Tetapi kita bisa belajar dari kolaborasi Microsoft dan Intel yang telah menyebabkan keduanya saling untung-untung. Dan ATM BCA bisa digunakan untuk membayar tagihan kartu kredit semua perbankan tanpa ada yang merasa dikalahkan.
Terkini, Co-opetition menjadi keniscayaan ketika Pfizer dan Bio Ntech pada Maret 2020 lalu sepakat mengembangkan vaksin covid-19. Kolaborasi itu memungkinkan kedua perusahaan farmasi untuk menggabungkan kemampuan pengembangan produk dan manufaktur. Kini, mereka mampu memasarkan vaksin pada akhir tahun 2020 dan telah memproduksi ratusan juta dosis pada tahun 2021. Di lapis media sosial, terjadi ko-opetisi antara situs kencan Tinder yang mencomot jejaring facebook atau Twitter. Amazon Prime dan Netflix, dua perusahaan yang bersaing ketat dalam konten platform streaming.
Semua serba mungkin untuk sebuah tujuan win-win solution. Co-opetition hanyalah tools untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang akan mempengaruhi para pemain untuk bersaing atau bekerja sama. Bukankah kita tidak perlu memadamkan lampu orang lain untuk membuat lampu kita sendiri bersinar. (Irsyad Muchtar)