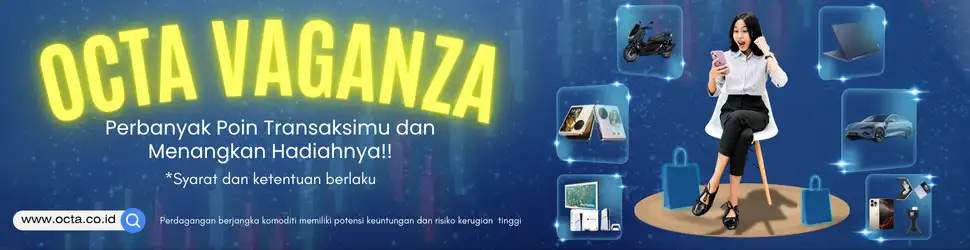Silsilahnya menunjukkan, Raja Kesultanan Sambas di abad ke-17 punya pertalian darah dengan Kesultanan Brunei Darussalam. Eksistensi kerajaan terbesar di Borneo barat hingga abad ke-19 ini berkelindan dan menyatu dengan Masjid Jami’ Kesultanan.
KOMPLEKS Istana Alwatzikoebilah didominasi warna kuning. Warna ini warna khas identitas bangsawan dalam budaya Melayu. Istana ini berada di Kota Sambas, ibu kota Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kota seluas 247 km²ini merupakan tempat pertemuan tiga sungai, yakni Sungai Subah, Sungai Sambas Kecil, dan Sungai Taberau. Mengingat sungai merupakan sarana transportasi utama di Kalimantan sejak dahoeloe kala, wajar jika istana memilih berlokasi di tepi sungai.
Istana Alwatzikoebilah terdiri dari bangunan utama berupa ruangan luas untuk menerima tamu, ruang tidur, dan ruang makan. Di sisi kiri kanan bangunan utama terdapat bangunan dimana salah satunya dulu digunakan sebagai dapur Kerajaan. Sisi kiri merupakan tempat penyimpanan pusaka Kerajaan. Harta benda Kesultanan Sambas yang masih bias disaksikan wisatawan saat ini di antaranya gong, payung, dan tombak serta meriam-meriam kecil.
Keluarga Kerajaan Sambas masih memiliki pertalian darah dengan keluarga Kerajaan Brunei Darussalam. Tatkala Kota Sambas ditetapkan menjadi ibu kota Kesultanan Sambas di abad 17, dan sejak itu mulai berkembang, Kerajaan Sambas dipimpin oleh Raja Sulaiman. Raja yang menyandang gelar Sultan Muhammad Shafiuddin ini tiada lain adalah putra adik Sultan Brunei yang memerintah di Sarawak.
Kesultanan Sambas itu kerajaan terbesar di pesisir barat Kalimantan yang berjaya sampai awal abad XIX. Namun kejayaannya mulai meredup saat Pemerintah Hindia Belanda–dibantu oleh pihak keluarga kerajaan yang berkhianat–berhasil melakukan kudeta. Ini adalah salah satu keberhasilan taktik pecah belah yang dilakukan Hindia Belanda di seluruh Nusantara. Sejak saat itu, peran Kesultanan Sambas dialihkan ke Kesultanan Pontianak bentukan Hindia Belanda.
Kerajaan yang bernama “Sambas” telah berdiri dan berkembang sebelum abad ke-14 M. Rajanya bergelar “Nek”. Setelah masa Nek Riuh, sekitar abad ke-15 M muncul pemerintahan raja yang bernama Tan Unggal terkenal sangat kejam. Ia dikudeta oleh rakyat. Akibatnya, puluhan tahun rakyat di wilayah Sungai Sambas ini tidak mau mengangkat raja. Pada masa vakum inilah, awal abad ke-16 M (1530) datang sekitar 500-an orang bangsawan Hindu Majapahit dari Jawa.
Rombongan ini menetap di hulu Sungai Sambas, di tempat yang sekarang disebut “Kota Lama”. Setelah 10 tahun lebih, mereka mendirikan sebuah kerajaan hindu bernama “Panembahan Sambas”. Raja lelaki Panembahan Sambas ini, Wikramawardhana, bergelar “Ratu”. Dari sinilah tradisi budaya Kerajaan Jawa mewarnai sebagian tradisi budaya Kesultanan Sambas. Gelar kebangsawanan “Uray” muncul pertama kali di masa Sultan Sambas ke-4 (Sultan Abubakar Kamaluddin). Sejak saat itu di Kesultanan Sambas mengenal dua gelar: “Raden” dan “Uray”.
Masa Keemasan Kesultanan Sambas terpatri atas nama Sultan Sambas ke-5, Sultan Umar Aqamaddin II. Raja ini dua kali memerintah, yang pertama (1762-1786) dan, setelah terhenti 7 tahun, dilanjutkan dengan masa kedua (1793-1802). Luas wilayah Kesultanan membentang dari Tanjung Datuk di utara hingga ke Sungai Duri, ke daerah Montraduk dan Bengkayang di tenggara, dan ke hingga daerah Seluas dan Sungkung—yang bertahan hingga Kesultanan Sambas bergabung ke dalam Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 1950.
Tahun 1812 M Kesultanan Sambas diserang pasukan Inggris atas perintah Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris di Batavia. Misi mereka gagal karena dipukul mundur oleh pasukan Kesultanan Sambas di bawah pimpinan Pangeran Anom. Setahun kemudian, pasukan Raffles kembali menyerang. Dengan jumlah pasukan yang lebih besar dan persiapan yang lebih baik, mereka berhasil.
Setelah Panembahan Sambas runtuh, Raden Sulaiman mendirikan kerajaan baru di Kota Lama, yaitu Kesultanan Sambas dengan gelar Sultan Muhammad Shafiuddin I, 1671. Wilayah kekuasaan Kesultanan Sambas terus meluas. Pada masa Sultan Sambas ke-4 (Sultan Abubakar Kamaluddin), wilayah itu utuh hingga berakhirnya masa pemerintahan Kesultanan Sambas selama sekitar 279 tahun (dengan melalui 15 orang Sultan dan 2 orang Kepala Pemerintahan) yaitu dengan bergabung ke dalam Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1950
Peninggalan dari jejak Kesultanan Sambas yang masih ada hingga saat ini adalah Masjid Jami’ Kesultanan Sambas, Istana Istana Alwatzikhubillah, Makam-makam Sultan Sambas sampai dengan Sultan Sambas ke-14, sebagian alat-alat kebesaran kerajaan seperti tempat tidur sultan terakhir, kaca hias, seperangkat alat untuk makan sirih, pakaian kebesaran sultan, payung ubur-ubur, tombak canggah, 3 buah meriam canon di depan istana dan 2 buah meriam lele, 2 buah tempayan keramik dari negeri Tiongkok dan 4 buah kaca cermin besar dari Kerajaan Prancis dan 2 buah kaca cermin besar dari Belanda.
Sebagian besar barang-barang peninggalan Kesultanan Sambas lainnya telah hilang atau terjual oleh oknum tertentu, namun secara fisik jejak Kesultanan Sambas masih terlihat jelas dan terasa kuat di Sambas ini. ●(dd)