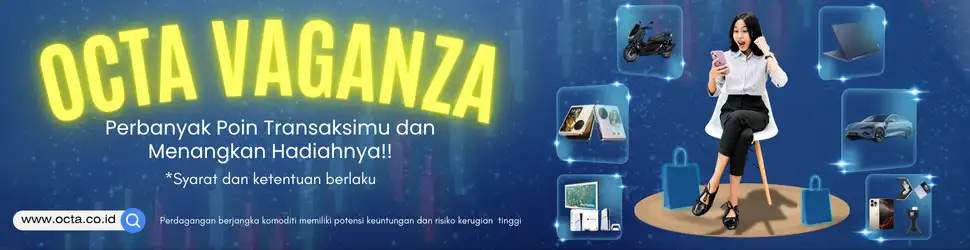Warga etnis Tionghoa di Bagansiapiapi melaksanakannya saban tahun. Ini upacara mengingat kisah heroik nenek moyang mereka. Perantau dari Fujian, mendarat di Bagansiapi-api, bertekad tak akan kembali ke tanah leluhur.
RITUAL Bakar Tongkang atau Upacara Bakar Tongkang atau dalam bahasa Hokkien dikenal Go Ge Cap Lak. Go Ge berarti bulan lunar yang kelima, Cap Lak berarti tanggal yang ke-16. Inilah ritual tahunan etnis Tionghoa di Bagansiapiapi, Riau, yang telah terkenal di mancanegara. Setiap tahunnya ritual ini mampu menyedot wisatawan dari Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan hingga Tiongkok Daratan.
Pembakaran kapal bermakna upacara peringatan terhadap dewa laut Ki Ong Yan dan Tai Su Ong yang merupakan sumber dua sisi, antara baik dan buruk, suka dan duka, serta rejeki dan malapetaka. Alkisah bermula dari tuntutan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Sekelompok orang Tionghoa dari Provinsi Fujian, Cina, bertolak merantau menyeberangi lautan dengan kapal kayu sederhana.
Dalam kebimbangan kehilangan arah, mereka berdoa kepada Dewa Kie Ong Ya agar diberikan penuntun arah menuju daratan. Muncul isyarat. Mereka pun bergerak menuju sumber cahaya yang tampak samar-samar dan mereka pun tiba di daratan Selat Malaka itu. Mereka yang mendarat di tanah tersebut sebanyak 18 orang, kesemuanya bermarga Ang atau Hong. Mereka inilah yang kemudian dianggap sebagai leluhur orang Tionghoa Bagansiapiapi.
Sebagai wujud terima kasih kepada dewa laut Kie Ong Ya, para perantau memutuskan untuk membakar Tongkang yang mereka tumpangi sebagai sesajen kepada dewa laut. Bakar Tongkang sekaligus mewujudkan peneguhan tekad mereka untuk tidak kembali ke tempat asal. Mereka sepakat menetap di tempat baru untuk mengawali lembaran hidup baru di tanah perantauan yang jauh dari tanah leluhur.
Pada penanggalan Imlek bulan kelima tanggal 16, para perantau menginjakkan kaki di daratan itu, mereka menyadari bahwa di sana terdapat banyak ikan laut. Dengan penuh sukacita mereka menangkap ikan untuk kebutuhan hidup. Harapan yang merupakan impian mereka menjelang berangkat kini tampak makin jadi kenyataan. Mereka tak hanya mampu bertahan hidup, tapi juga secara perlahan makin sejahtera.
Mereka yang merasa menemukan daerah tempat tinggal yang lebih baik segera mengajak sanak-keluarga dari Negeri Tirai Bambu. Lama kelamaan, jumlah pendatang Tionghoa semakin banyak. Keahlian menangkap ikan yang dimiliki nelayan tersebut menghasilkan jumlah tangkapan yang terus berlimpah. Hasil laut berlimpah tersebut diekspor ke berbagai benua lain, hingga Bagansiapiapi saat ini menjadi penghasil ikan laut terbesar kedua di dunia, setelah Norwegia.
Semakin ramainya kegiatan perdagangan di Selat Melaka mendorong Belanda melirik Bagansiapiapi. Wilayah ini dinilai strategis untuk menjadi salah satu basis kekuatan laut. Pihak kolonial dari Negeri Kincir Angin itu pun membangun pelabuhan di Bagansiapiapi. Konon, pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan paling canggih saat itu di Selat Melaka.
Selain ikan, hasil karet alam yang juga sangat terkenal. Pada masa Perang Dunia I dan Perang Dunia II, Bagansiapiapi merupakan salah satu daerah penghasil karet berkualitas tinggi yang saat itu banyak dipakai untuk kebutuhan peralatan perang, seperti ban. Pengolahan karet alam di daerah ini dilakukan sendiri oleh masyarakat setempat di beberapa pabrik karet di Bagansiapiapi.
Dari sisi kebudayaan, terdapat sebuah kelenteng tua yang sudah berumur ratusan tahun. Di tempat kelenteng inilah Dewa Kie Ong Ya saat ini disembahyangkan. Dewa Kie Ong Yayang ada di dalam kelenteng Ing Hok Kiong saat ini adalah patung asli yang dibawa ke-18 perantau pada saat pertama kali menginjak kaki di daratan Bagansiapiapi.
Kembali ke Bakar Tongkang, inti terpenting dalam peringatan yang terkait dengan sejarah perjalanan leluhur etnis Tionghoa yakni ungkapan rasa terima kasih kepada ke-18 leluhur mereka. Mereka mengenang peristiwa bersejarah itu sebagai peristiwa heroik penyebab mereka bisa menetap di Bagansiapiapi sampai saat ini.
Bagi warga Tionghoa asal Bagansiapiapi yang sukses merantau ke kota/daerah lain akan berupaya datang menyaksikan ritual leluhur ini. Bagaimanapun, kegiatan yang dianggap sakral ini memberi kepuasan batin yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang terlibat. Manfaat yang diharapkan warga Tionghoa dalam perayaan ini adalah semakin sukses (keuangan) dalam meniti kehidupan.
Biaya pelaksaan kegiatan ritual tahunan ini tidak sedikit. Selama ini, tradisi Bakar Tongkang terselenggara antara lain berkat sumbangsih para donatur. Baik itu dari negeri leluhur dan warga keturunan di Jakarta maupun bersumber dari dermawan negara lain seperti Amerika, Inggris, Malaysia, Singapura, dan Taiwan yang peduli terhadap arti penting ikhtiar pengawetan tradisi masyarakat.
Ritual ini merupakan salah satu tradisi di Riau yang telah masuk dalam kalender visit Indonesia. Di mancanegara pun—sebut saja Malaysia, Taiwan, Thailand, Singapura—upacara Bakar Tongkang Bagansiapiapi ini sama sekali bukan hal yang asing. Mereka menjadi bagian pasif setiap upacara ini digelar, setiap tanggal ke-16 bulan kelima menurut sistem penanggalan lunar.
Di masa Orde Baru, Upacara Ritual Bakar Tongkang Bagansiapiapi dilarang selama puluhan tahun. Maklum, Soeharto tidak mengizinkan segala bentuk ekspresi sosiokultural yang berbau Cina. Setelah tahun 2000, tradisi ini diaktifkan kembali. Bukan tanpa alasan jika event tahunan ini gencar dipromosikan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebagai salah satu ikon pariwisata Provinsi Riau. (Nay)